- Polusi Udara Meningkatkan Risiko dan Memperburuk Kondisi Penderita MND
- Sistem Pertahanan Tubuh Dapat Menentukan Seberapa Sakit Kita Saat Terserang Flu
- Aspek Hukum Clear, KPK Dukung KemenPKP Optimalkan Lahan Meikarta untuk Rusun Bersubsidi
- BRIN - OceanX Identifikasi 14 Spesies Megafauna dan Petakan Gunung Bawah Laut Sulawesi Utara
- Bantuan Bencana Sumatera Didominasi Makanan Instan, Kesehatan Anak Jadi Taruhan
- Krisis Makna di Balik Identitas Starbucks di Era Digital
- Mengapa Komunikasi PAM Jaya Perlu Berubah
- Krisis BBM Pertamina, Ketika Reputasi, Identitas, dan Kepercayaan Publik Bertabrakan
- Greenpeace-WALHI: Pencabutan 28 Izin Perusahaan Pasca Banjir Sumatera Harus Transparan dan Tuntas
- KemenPU Susun Rencana Rehabilitasi 23 Muara Sungai Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Istri, Logo, Buku
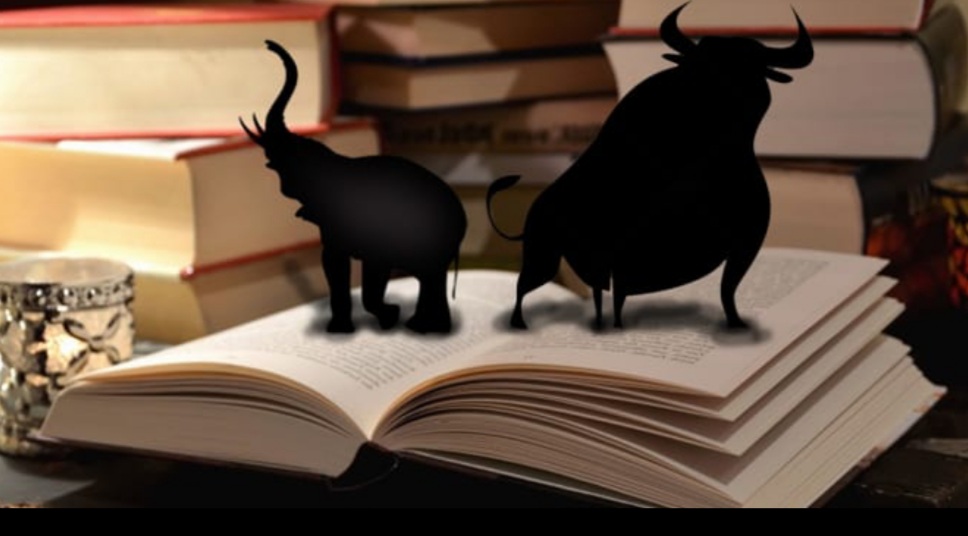
Bandung Mawardi
Tukang kliping, bapak rumah tangga
ORANG-ORANG masih mengenang Chairil Anwar. Ia tetap dijuluki “binatang jalang.” Di sastra Indonesia, ia bukan ahli menggubah puisi bertema binatang. Ia memang mengerti binatang untuk masuk dalam larik-larik puisi tanpa maksud menjadi pengajaran satwa. Di sekolah, Chairil Anwar diakrabi dengan puisi-puisi, bukan pengamat binatang. Ia tak berjanji membuat album puisi menguak zoologi.
Kita mungkin agak melupakan keanehan Chairil Anwar dalam lakon keluarga. Ia memiliki panggilan khas untuk istri: “gajah”. Lelaki kurus dan bermata tajam itu mengucap gajah bisa menimbulkan imajinasi kasih, ejekan, lelucon, atau mesra. Istri dipanggil “gajah” membuat kita penasaran dengan mutu asmara ditanggungkan Chairil Anwar dan siasat berbahasa dalam situasi tak keruan (1940-an). Konon, panggilan “gajah” berdasarkan tampilan raga. Pengarang suka merokok itu tega!
Di biografi tokoh-tokoh besar di Indonesia, sebutan atau julukan menggunakan satwa lazim terjadi sejak lama. Kartini saja pernah mendapat panggilan “trinil”, mengingatkan kuda. Sebutan indah mungkin milik Rendra. Orang-orang kadang menjuluki “si burung merak”. Kita mengerti biografi orang mengandung masalah fauna secara kebahasaan, sifat, dan nasib.
Pada abad XXI, kita dapat pengajaran gajah. Kita tak lagi memasalahkan sebutan, panggilan, atau julukan merujuk tokoh-tokoh masa lalu. Gajah dimunculkan PSI berkepentingan politik. Perubahan logo oleh PSI menimbulkan beragam tafsiran. Kaesang berusaha memberi penjelasan. Kita menganggap itu “kecerewetan” demi mendapat pengakuan.
Di kubu berbeda, lawan politik atau pengamat politik pun sibuk adu tafsir. Mereka memikirkan gajah. Kesadaran telah terbentuk lama: binatang masuk politik. Kita mengingat masa 1920-an, saat kaum muda Indonesia di Belanda mulai menggunakan bendera merah putih dengan kepala kerbau di tengah. Pada situasi dan kepentingan berbeda, partai politik dan perkumpulan pun menggunakan gambar binatang.
Fauna tampak mengungguli flora dalam propaganda politik. Kita diajak belajar lagi tentang binatang tapi mengarah ke urusan kekuasaan. Para tokoh politik kadang mengumumkan pilihan gambar binatang merujuk sejarah atau pemantapan filosofi. Kita dibuat bingung tanpa sempat melakukan pengamatan bintang-binatang di seantero Indonesia. Kini, gajah bikin ramai. Perhatian terhadap gajah dan PSI mungkin sejenis “hiburan picisan” sebelum muncul gegeran baru berkaitan logo resmi peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Kita tak mau selalu politis ingin menambahi pengetahuan dengan membaca buku-buku bertema fauna. Kita tak kembali ke buku pelajaran saat SD. Perkara binatang dalam pengajaran di sekolah terbukti “sedikit” dan sulit berdampak. Di Indonesia, masalah-masalah binatang (mau) punah itu selalu tersiar. Para murid justru memilih belajar binatang melalui film-film (sering) buatan negara-negara asing. Pengetahuan binatang-binatang di Nusantara mudah terbatasi dalam buku pelajaran dan kunjungan ke kebun binatang.
Kita membuka buku tipis berjudul Empat Raja Rimba Indonesia (1975) susunan Prof Dr Garnadi Prawirosudirdjo. Profesor sengaja membuat buku sederhana agar dipahami anak-anak. “Dan, mengungkapkan keajaiban atau rahasia alam adalah tujuan para ahli binatang dan para pencinta alam,” tulis sang profesor. Ia sedang mengingatkan studi-studi binatang di Indonesia sering dilakukan para sarjana dan peneliti asing. Buku-buku mereka terbit dalam pelbagai bahasa asing, sedikit saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Penjelasan disampaikan secara enteng dan sederhana: “Lucu benar nampaknya kalau gajah itu mengambil makanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Cekatan dan tak pernah salah ia dalam menggunakan belalainya. Teranglah bahwa belalai itu alat yang baik dan ujungnya adalah alat perasa yang amat beka.” Lumrah saja anak-anak suka membaca cerita-bergambar atau komik bertokoh gajah. Mereka pun ketagihan menonton film menampilkan kelucuan dan kegagahan gajah.
Di Indonesia, anak-anak jarang diajak belajar gajah bersumber sejarah. Sang profesor bukan ahli sejarah tapi berhak mengingatkan: “Orang-orang Belanda mula-mula tiba di Aceh dalam tahun 1598. Mereka melihat di sana para bangsawan yang mengendarai gajah waktu ada perayaan penting. Ada buku-buku China yang menceritakan bahwa raja-raja Jawa dahulu mengendarai gajah. Di Candi Borobudur, terdapat lukisan-lukisan gajah di dinding.” Di buku tipis, sang profesor memastikan gajah itu “raja rimba” bersama harimau, banteng, dan badak.
Kita masih bisa belajar lagi melalui buku berjudul Khazanah Flora dan Fauna Nusantara (1992) terbitan YOI. Di situ, Bintaro menerangkan: “Gajah Sumatera merupakan satwa langka kebanggaan nasional. Mamalia besar di Indonesia dilindungi undang-undang sejak tahun 1931. Gajah Sumatera merupakan salah satu dari tiga anak-jenis gajah yang hidup di Asia.” Pengetahuan penting bagi publik meski condong tertarik dengan berita mengenai perburuan gajah demi mendapatkan gading atau gajah mengamuk di permukiman warga.
Di Indonesia, usaha memberikan hak hidup gajah sering bertabrakan dengan kepentingan pembuatan lahan perkebunan dan permukiman. Masalah-masalah muncul dengan akibat-akibat buruk. Gajah dalam keterbatasan atau kesempitan untuk ruang hidup. Penebangan pohon-pohon di hutan atau alih fungsi hutan makin mengecewakan gajah. Mereka berhak marah. Kita seolah mengenali gajah tapi terbiasa telat menginsafi derita gajah. Pada abad XXI bertajuk penghancuran alam, nasib gajah makin rawan.
Kini, kita belajar (logo) gajah dalam pamrih politik. Gajah itu berada di bendera, kaos, jaket, dan spanduk. Gajah bukan dalam kelucuan di mata anak-anak. Gajah jauh dari (imajinasi) sejarah Nusantara. Gajah itu berwarna merah-putih, mustahil ditemukan di hutan atau kebun binatang. Begitu.


.jpg)
1.jpg)

.jpg)


1.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)

