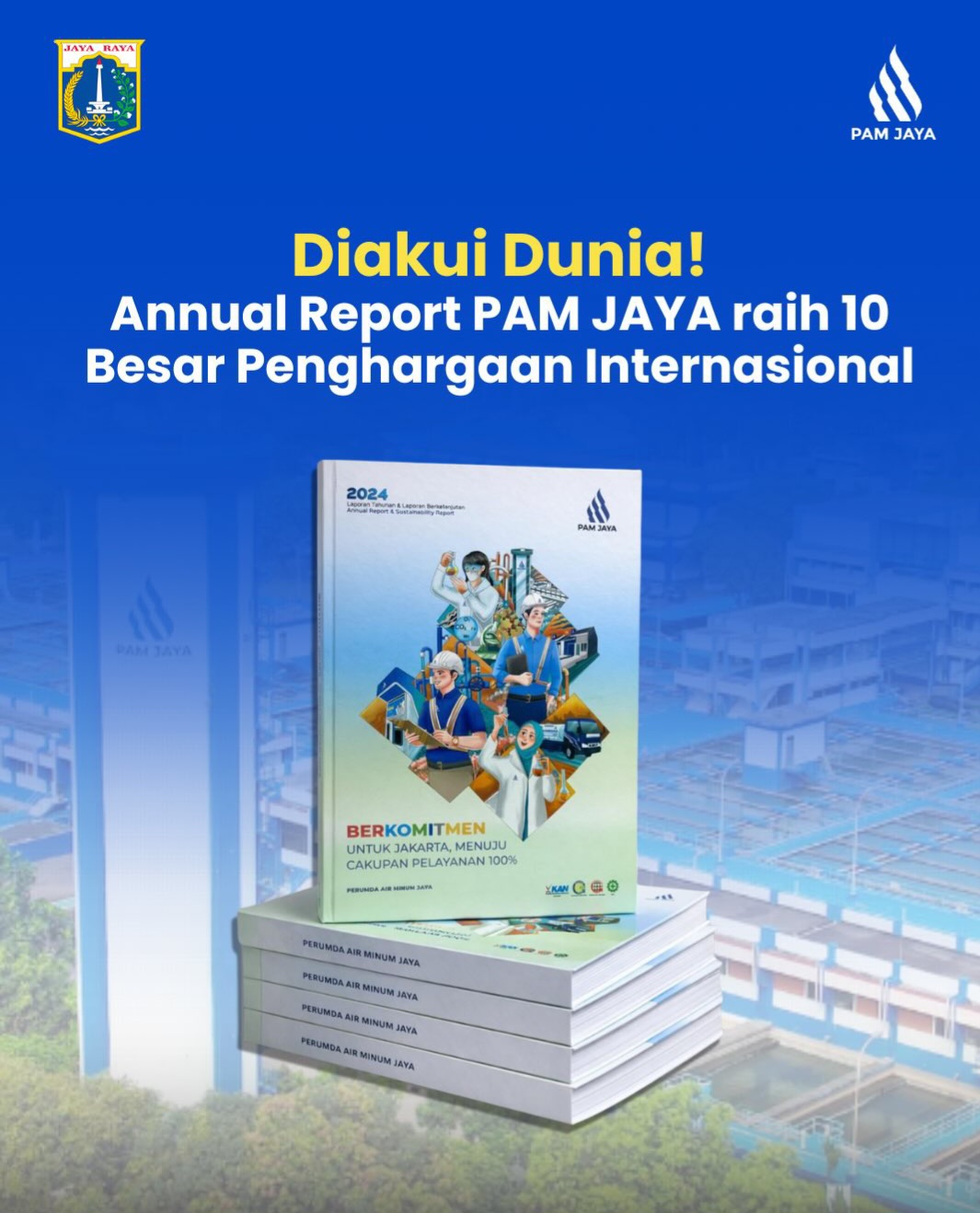Kepala: Trump dan Indonesia
1.jpg)
Bandung Mawardi
Tukang kliping, bapak rumah tangga
Baca Juga
DI Iran, tersiar kabar menantang.
Seorang ulama menawarkan duit belasan miliar rupiah. Duit imbalan untuk orang
berani membunuh Donald Trump. Bukti kematian Trump: kepala dibawa ke Iran.
Permusuhan belum selesai. Kematian penguasa Amerika Serikat itu dikehendaki
agar dunia tak makin kisruh.
Trump bukan manusia “biasa”. Ia suka omong dan pamer
kekuasaan. Orang-orang tergiur duit miliaran rupiah atau bermisi menata ulang
politik dunia wajib memikirkan jurus paling ampuh. Usaha mendapatkan kepala
Trump tak seperti permainan dalam gawai. Trump memiliki tentara, senjata, dan
teknologi untuk menghindari orang-orang bermaksud membunuh dan mendapatkan
kepala untuk dibawa ke Iran.
Kita membaca kabar itu mirip lelucon pahit. Trump telah
membuat dunia amburadul. Iran tak gentar. Bermusuhan dengan Amerika Serikat itu
kepastian untuk raihan kemenangan. Kita di Indonesia menunduk malu gara-gara
mengetahui ketangguhan Iran berhadapan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Indonesia sedang pusing dan ruwet, belum ada gelagat ikut meramaikan gegeran
dunia. Indonesia malah dikutuk debat-debat tiada henti.
Sekian bulan lalu, debat besar di Indonesia bertema kepala.
Debat itu berlalu tergantikan debat-debat makin membuat jutaan orang pusing.
Hidup di Indonesia, hidup dengan seribu perdebatan untuk urusan-urusan sepele
dan genting. Hari-hari riuh kata. Orang-orang bernafsu dalam tuduhan, bantahan,
makian, pujian, dan lain-lain. Debat-debat di Indonesia sulit menjadi bukti
kematangan berdemokrasi. Kita mulai mengerti gelaran debat-debat di pelbagai
tempat justru menjadi selebrasi kemustahilan berdemokrasi.
Di buku Neksus (2025) garapan Noah, kita diajak
memasalahkan informasi-informasi diproduksi dalam kelimpahan dan bersebaran ke
segala arah Di situ, ada pihak-pihak sempat mengukuhkan kebenaran. Di seberang,
orang-orang insaf terjadi jalinan-jalinan mengejutkan dalam ikhtiar mengerti
beragam perkara: politik, agama, hiburan, makanan, dan lain-lain. Petaka-petaka
dipicu bah informasi menimbulkan retak, sesat, runtuh, ilusif, kacau, buram,
dan renggang. Pengharapan atas kebaikan, kebenaran, ketulusan, atau keadilan
tampak menciut.
Seribu peringatan atas keterpurukan hidup dalam abad XXI
jarang mendapat perhatian. Kemunculan rombongan tanda seru justru dipandang
dengan kelakar. Kita memastikan debat-debat tak keruan di Indonesia memang
bertumpu jalinan dan edaran informasi-informasi untuk adu kemenangan.
Kebohongan dan hasutan menambahi bobot keruwetan debat. Peningkatan jumlah
omelan atau bantahan memungkinkan peminggiran kebenaran. Kita telanjur
mengalami hari-hari ramai debat berakibat lupa puisi.
Kita membaca “Puisi Kubangan” gubahan Emha Ainun Nadjib
(1994) saat masih muda. Ia berpuisi dalam lakon Orde Baru. Indonesia lelah oleh
seribu perintah Soeharto. Indonesia tersandung janji. Indonesia dipaksa putus
asa. Emha mengerti dan mengamati untuk mengingatkan:
Engkau menikmati jari-jemarimu memainkan seribu/ wayang,
engkau gerakan ke kiri dan ke kanan, engkau/ gebug dan lemparkan, tanpa
hari-hari menjelang ajal bisa/ menghentikanmu. Engkau menyangka sedang
berpesta/ kekuasaan, kepandaian dan harta, sedangkan yang/ engkau lakukan
sebenarnya adalah membuang habis/ jatah hari depanmu sendiri di dalam kehidupan
yang/ sesungguhnya. Kita membaca lari-larik itu sambil mengenang masa kekuasaan
Soeharto.
Kini, Emha mungkin tak lagi menggubah puisi dengan kekuatan
seperti silam. Ia menua dan raga tak lagi kokoh. Cara berbahasa berubah meski
ia mengerti Indonesia makin sulit bermimpi indah. Di “Puisi Seadanya Mengenai
Kepala”, Emha (1994) suguhkan humor menggelap kepada para pembaca: Jangan salah
sangka. Ia takut bukan karena khawatir akan/ kehilangan kepala, melainkan
justru ia sangat/ mendambakan betapa bahagianya kalau pada suatu hari ia/
kehilangan kepala.
Ia melakukan kritik telak atas keinginan menjadi Indonesia.
Kepala bukan jaminan waras. Indonesia memiliki kepala negara tapi nasib jutaan
orang berada di kaki. Orang-orang diminta belajar agar berkepala pintar tapi
Indonesia dijerat kebodohan dan kebebalan. Kepala tak lagi mengisahkan
kehormatan. Di Indonesia, kepala-kepala menjadi kepongahan dan kehancuran.
Emha berkelakar ingin kehilangan kepala. Ia tak sedang
meremehkan atau memaki orang lain. Emha merenungi keinginan kehilangan kepala:
Tuhan/ sendiri sepertinya terlalu bersabar dan menyimpan teka-teki ini,/ bahkan
sesekali ia merasakan Tuhan seakan-akan bersikap/ ogah-ogahan terhadap masalah
ini.
Permintaan aneh menantikan tanggapan Tuhan. Emha terlalu
berani memasalahkan kepala: Apa jawab/ penyair kita ini seandainya Tuhan
mengucapkan/ argumentasi begini: “Bagaimana mungkin kuganti/ kepalamu,
sedangkan kepala-kepala lain di tangan-Ku belum/ punya pengalaman sama sekali
untuk bertindak sebagai/ kepala? Bukankah untuk menjadi kepala, segumpal
kepala/ harus memiliki pengalaman sebagai kepala/ sekurang-kurangnnya lima
tahun?”
Dulu, orang-orang membaca puisi gubahan Emha sebagai
keberanian dan kurang ajar. Kini, kita tergoda lagi mengutip dan membahas saat
lakon kekuasaan terbaru sempat dimulai dengan debat tentang kepala terucap
dalam bahasa Jawa.
Kita bisa menafsir kepala itu berada di atas. Kepala menjadi
pihak tertinggi. Emha justru merasa lelah dan kecewa dengan kepala. Puisi itu
terbaca saat kita memiliki halaman-halaman sejarah politik sangat ditentukan
oleh kepala (negara) atau kepala (pemerintahan). Lakon bertajuk demokrasi
memang menempatkan seseorang di derajat tinggi dengan sebutan kepala. Konon,
sosok sebagai “kepala” haru memiliki kebijaksanaan agar kekuasaan itu baik,
indah, dan adil.
Emha Ainun Nadjib terbiasa menulis puisi mengenai kepala.
Kita bisa membaca lagi sambil mengikuti dampak kabar dari Iran. Kita
berimajinasi kepala Trump. Kepala itu berpengaruh di dunia meski kita
menganggap mustahil untuk keberhasilan pembunuhan Trump.
Kita membaca saja “Syair Seonggok Kepala” gubahan Emha Ainun
Nadjib (1983). Puisi tak ada kaitan dengan demokratisasi di Indonesia dan
impian atas kematian Trump. Enam larik menghasilkan renungan ringan: Di depan
pintu rumahku, pagi itu/ Tergeletak seonggok kepala// Orang-orang berkerumun/
Dan tersenyum-senyum// Berbinar-binar cahaya mata mereka/ Beberapa orang
membayangkan bermain bola.
Trump berkuasa di Amerika Serikat. Di sana,
pertandingan-pertandingan sepak bola digelar di pelbagai stadion. Ribuan orang
menonton bola menggelinding atau terbang. Bola itu bola. Bola bukan kepala
(Trump). Di Stadion MetLife, Amerika Serikat, 14 Juli 2025, Trump menjadi
penonton.
Konon, Trump mendapat sorakan dan siulan mengandung ejekan.
Penguasa itu menjadi saksi PSG dihajar Chelsea. Ia jeda sejenak dari kesibukan
membikin onar di dunia. Puisi lawas gubahan Emha Ainun Nadjib itu tak berkaitan
dengan Trump, meski kita bisa membaca dan merenungkan pemandangan seonggok
kepala tergeletak di depan pintu. Kepala itu kekuasaan. Kepala pun bukti kalah
dan tamat. Begitu.

1.jpg)


.jpg)