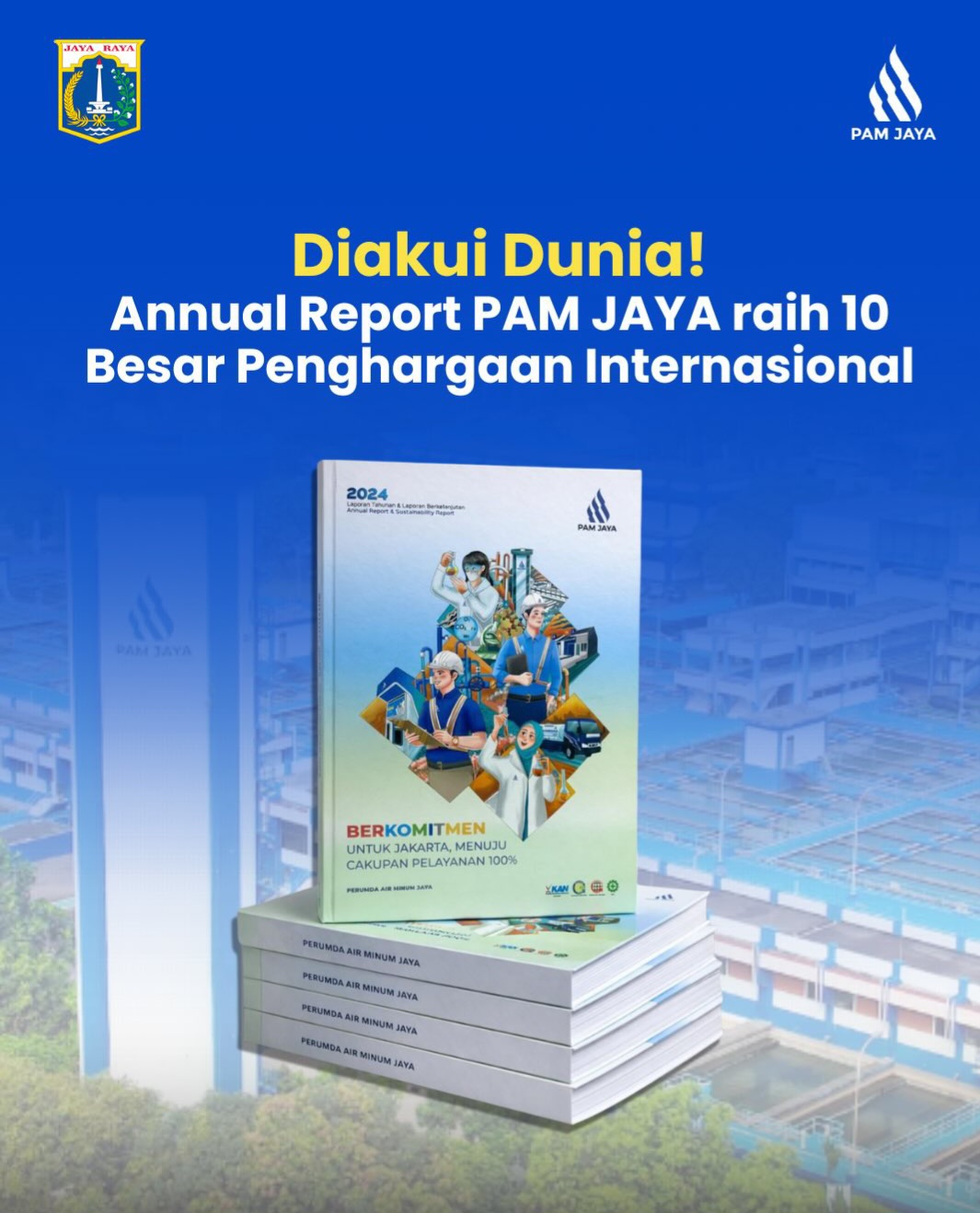Garis yang Mencari Ibu

Dwi Sutarjantono
Pemerhati Seni dan Gaya Hidup, Sekretaris Umum
Satupena Jakarta
Baca Juga
DALAM tradisi seni rupa, drawing
sering dianggap sebagai medan awal perang sekaligus medan tersulit. Ia tidak
memberi tempat bersembunyi. Setiap garis adalah keputusan yang tak dapat
ditarik kembali. Setiap goresan adalah konsekuensi dari keberanian untuk jujur.
Karya-karya Bambang Asrini Wijanarko membuktikannya dengan terang dan gelap
yang tak berpura-pura.
Melihat karyanya, kita seakan dihadapkan pada kejujuran yang tidak bisa dinegosiasikan. Kejujuran yang lahir dari pertempuran batin, dari dunia yang kadang terlalu keras, dan dari luka-luka yang tidak pernah tertutup rapat. Pada pandangan pertama, saya menemukan gema warisan besar para perupa dunia. Ketegangan anatomis ala Egon Schiele pada bentuk tangan, lirihnya kelam Käthe Kollwitz, juga bayangan pekat yang mengingatkan pada fase-fase gelap Goya.

Rasanya apa yang ditawarkan Bambang bahkan melampaui rujukan
sejarah itu. Ia membangun bahasanya sendiri. Bahasa garis yang seperti catatan
harian, seperti napas yang berat, seperti langkah yang terus bergerak meski tak
selalu tahu ke mana harus pulang.
Garis-garisnya tidak pernah lurus sepenuhnya. Selalu ada
getaran, ketidaksempurnaan, dan patahan kecil yang justru memberi nyawa. Dalam
hitam-putih karya-karyanya, dua dunia saling menantang: putih sebagai ruang
sunyi tempat ingatan mengendap, dan hitam sebagai gelap yang mengekalkan duka.
Jika muncul warna lain seperti merah, sesedikit apa pun itu, ia menyentak seperti detak jantung terakhir dari sesuatu yang ingin dipertahankan. Merah yang tidak menuntut perhatian, tetapi justru menjadi pusat gravitasi emosional dalam setiap helai gambar.
Merahnya Bambang adalah sisa-sisa luka.
Merah itu adalah sisa-sisa doa.
Merah itu adalah jejak seseorang yang hilang, namun tak
pernah pergi dari hatinya.
Untuk memahami sepenuhnya apa yang kita lihat, kita perlu
menoleh pada sosok manusia di balik karya. Bambang: kurator, seniman, sahabat
yang saya kenal bukan hanya melalui karyanya, tetapi melalui ketegarannya
menahan badai hidup yang tidak selalu adil baginya.
Dalam setiap obrolan kami, saya menyaksikan sisi lain
dirinya: sisi yang tidak banyak orang tahu. Ia tampak kokoh di luar, namun
membawa perang sunyi di dalam. Masalah-masalah pribadi, pergulatan identitas,
perjalanan hidup yang berliku. Semua itu adalah palung yang berkali-kali
menariknya jatuh. Namun di tengah segala itu ada satu hal yang tidak pernah
berubah: ibunya.
Cinta seorang anak kepada ibunya sering hadir dalam bentuk
yang tidak puitis, tetapi pada diri Bambang, cinta itu menjadi poros hidupnya.
Ia selalu menempatkan ibunya di atas segalanya, bahkan di atas dirinya sendiri.
Jika boleh disuarakan, barangkali ini sumpah yang selama ini ia pegang:
“Biarlah aku yang berdarah-darah. Asal jangan Ibuku.”

Dan garis-garis pada kertas ini: hitam, putih, (dan merah)
seolah mewujudkan kalimatnya. Seolah ia menggambar dirinya sendiri yang retak,
remuk, dan terluka, demi menjaga seseorang yang menjadi cahaya satu-satunya.
Dalam beberapa karya, bentuk-bentuk yang mengingatkan pada rahim atau organ
kewanitaan muncul secara intuitif seperti simbol asal kehidupan, asal cinta,
dan asal kehilangan.
Pada titik tertentu, pameran bertajuk Motherland ini
adalah bentuk cintanya pada sang ibu yang meresap menjadi cinta pada tanah air:
Ibu Pertiwi. Situasi negeri ini, dengan segala luka yang belum sembuh, seperti
bercermin pada hatinya sendiri.
Saat ibunya wafat, dunia Bambang runtuh dalam senyap. Bukan
kehancuran yang berteriak, tetapi kehancuran yang diam, mencekik, dan merampas
arah. Saya melihat sendiri bagaimana separuh jiwanya seperti hilang bahkan
mungkin lebih dari separuh. Ia berjalan, bekerja, menggambar… tetapi selalu ada
ruang kosong di balik setiap gerakannya. Ruang kosong yang kini menjelma
menjadi bagian dari estetika karyanya.
Maka, saya membaca pameran ini bukan sekadar rangkaian drawing.
Ia adalah ritual berduka.
Ia adalah surat yang ditulis dengan garis, bukan kata. Ia
adalah cara seorang anak kembali ke pangkuan ibunya, meski hanya di dalam
ingatan.
Perhatikan tiap goresan pensil, bambu, atau tinta, ada getaran kehilangan. Ada bayangan tubuh yang seakan hendak lenyap. Ada wajah tanpa kontur, seolah waktu telah menggerusnya. Ada merah yang hadir seperti tetesan darah, tapi juga seperti bibir yang mendoakan seseorang yang dicintai dengan seluruh hidupnya.

Melihat drawing-drawing ini, kita tidak hanya membaca
karya seni. Kita membaca hidup seseorang. Kita membaca cinta yang tidak pernah
surut, meski dunia merenggut orang yang menjadi pusatnya.
Pameran ini, pada akhirnya, adalah persembahan. Persembahan
seorang anak kepada ibunya. Persembahan seorang seniman kepada luka yang
membentuknya. Persembahan seorang manusia kepada hal-hal yang tidak sempat ia
ucapkan. Persembahan seorang anak negeri kepada Ibu Pertiwi.
Bambang mengingatkan kita bahwa garis pada kertas dapat
menjadi jembatan antara yang hidup dan yang telah pergi. Bahwa seni bisa
menjadi rumah ketika dunia tidak lagi ramah. Bahwa kehilangan, betapapun
menyakitkan, dapat melahirkan keindahan yang membuat kita mengerti sedikit
lebih banyak tentang apa artinya menjadi manusia.
Dalam keheningan karya-karya Bambang ini, mari kita
dengarkan suara yang ia sisakan. Suara yang mungkin ia tujukan kepada ibunya,
dan mungkin juga kepada kita dan ibu kita, atau kepada negeri ini: Ibu Pertiwi.
Singkat kata pameran ini menyadarkan kita bahwa cinta tidak
pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk: menjadi garis, menjadi
bayang, menjadi ingatan.

1.jpg)


.jpg)