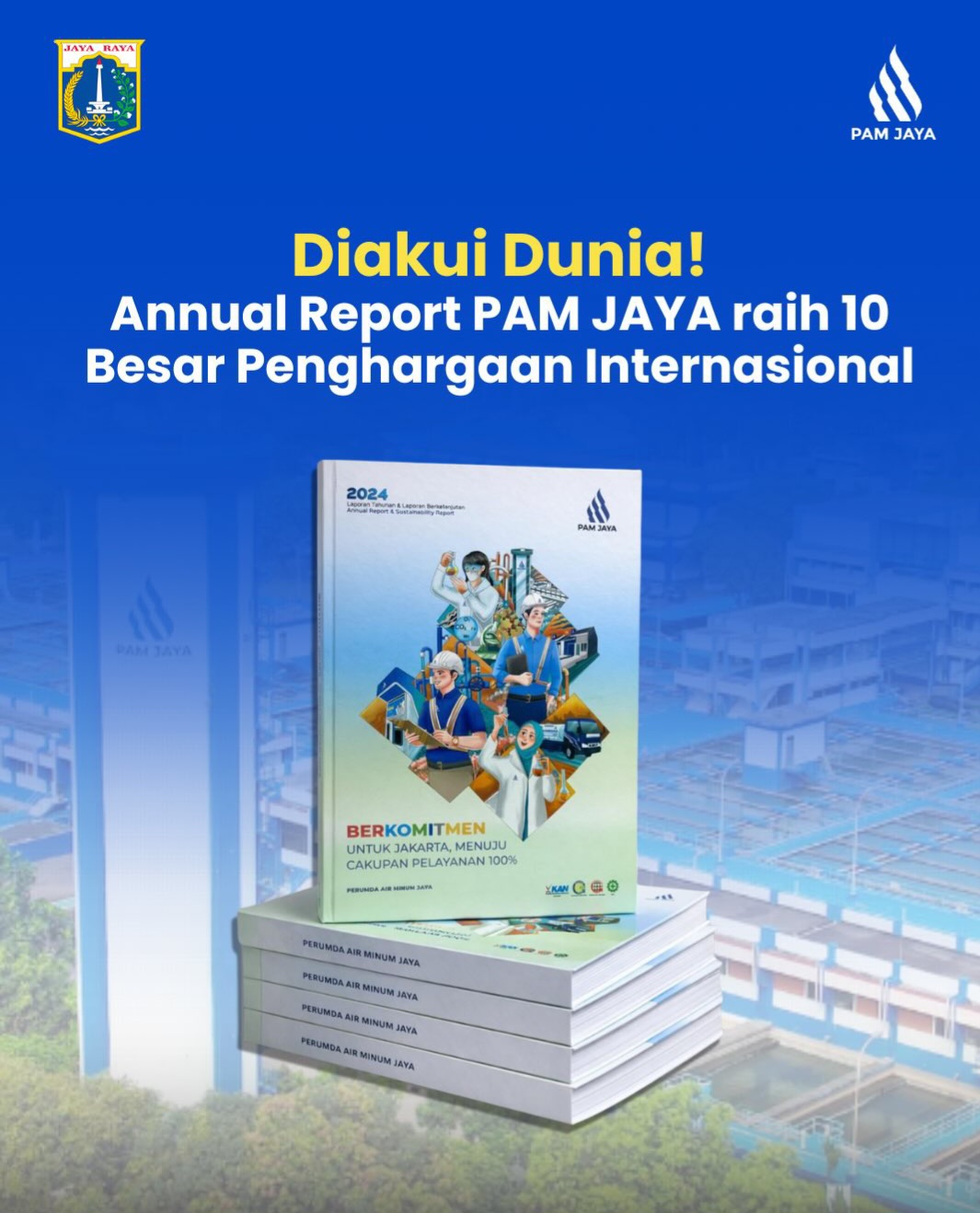Bencana di Sumatera: Negara Harus Tegas, Hukum dan Cabut Ijin Perusahaan Perusak Lingkungan
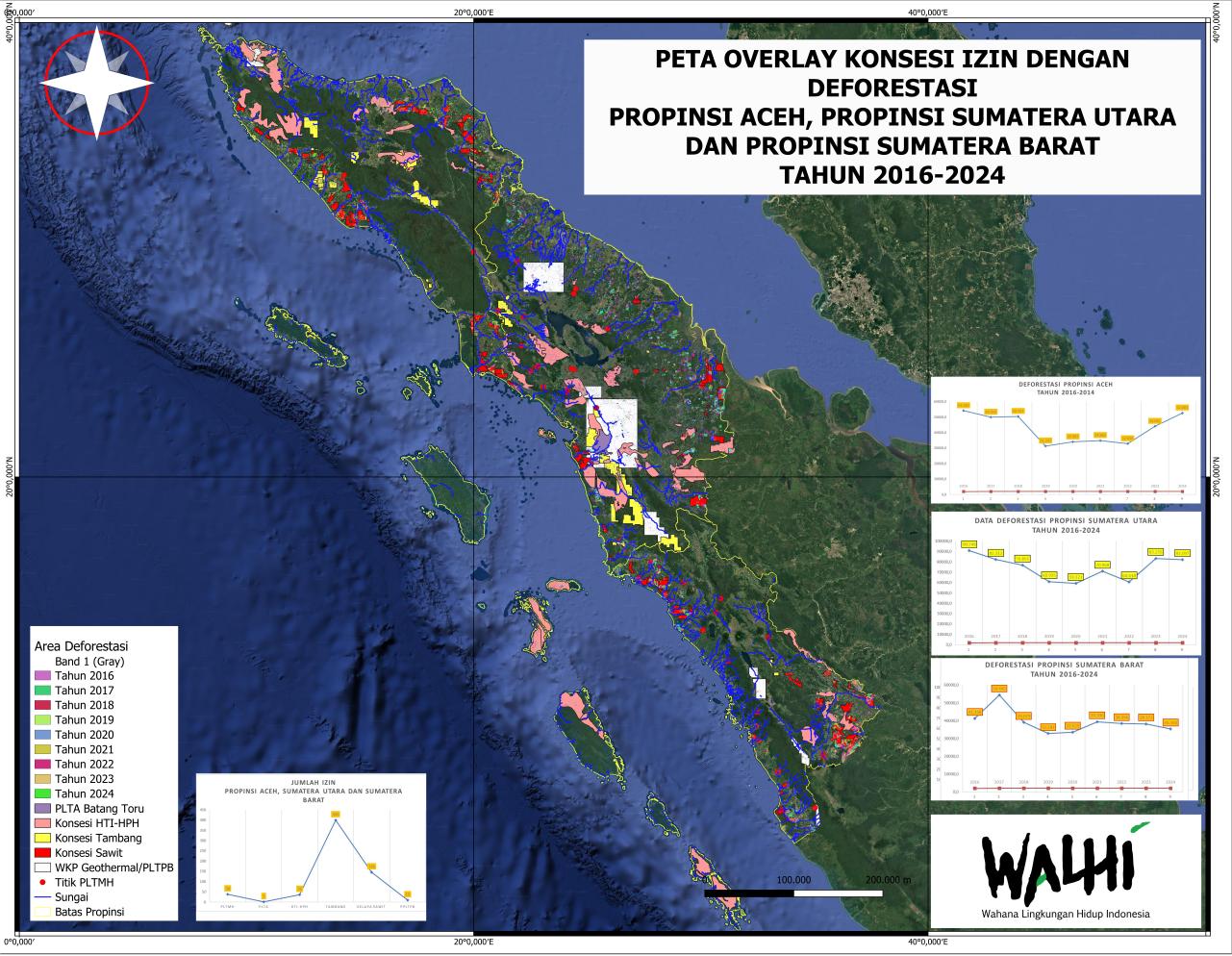
JAKARTA - Banjir dan longsor yang
menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November lalu
menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 orang harus
mengungsi. Berdasarkan catatan WALHI, bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis
yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan,
dan diperparah oleh krisis iklim.
Periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektare hutan di
Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas
631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan
PLTM. Jika dilihat lebih detail, bencana di tiga provinsi ini bersumber dari
wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang hulu-nya berada di bentang hutan
Bukit Barisan.
Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda
wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang
Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan
Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah
mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar (2016-2024) akibat operasi 18
perusahaan.
Baca Juga
Sedangkan di Aceh, ada 954 DAS, 60% dalam Kawasan Hutan, 20
DAS kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Trumon yang memiliki luas 53.824
Ha. Sejak 2016-2022 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan,
sekarang tersisa 30.568 Ha atau sekitar 57%. DAS Singkil sebagaimana yang
ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 1,241,775 hektar. Namun sisa
tutupan hutan pada 2022 hanya 421,531 hektar.
Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami
degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820,243 hektar, 66%. DAS Jambo
Aye luas awalnya 479.451 hektar, kerusakan 44,71%. DAS Peusangan yang luasnya
245.323 kerusakan 75,04%, DAS Krueng Tripa dari total luas 313.799 kerusakan
42,42%. DAS Tamiang dari luas 494.988 kerusakan 36.45%.
Di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin yang merupakan salah satu
DAS administratif penting di Kota Padang, dengan luas 12.802 hektar. Secara
topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal, dengan
bagian hulu berada di wilayah kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang
seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama.
Namun, kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan
aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aia Dingin kehilangan 780
hektar tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu, yang
memiliki peran vital dalam meredam aliran permukaan dan mencegah banjir
bandang.
Ahmad Solihin Direktur Eksekutif
Daerah WALHI Aceh mengatakan, banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16
kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras, bahwa alam tidak lagi mampu
menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Bencana kali ini bukan hanya
fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan
pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup
masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang.
“Banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari
deforestasi, ekspansi sawit, hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang
dibiarkan merajalela. Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan
terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti
pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai.”
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara Riandra
Purba, menyampaikan, wilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah,
Sibolga dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam
delapan tahun terakhir WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan
Batang Toru. Misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan
dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di
sungai Batang Toru. Desa-desa lain di kecamatan Sipirok juga ada aktivitas
kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya
mengalihfungsikan hutan. Semua aktitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah
melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang.”
Andre Bustamar dari WALHI Sumbar
menyatakan, bahwa penyebab bencana di Sumbar diakibatkan oleh akumulasi
krisis lingkungan karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan SDA.
Deforestasi, pertambangan emas ilegal, lemahnya penegakan hukum menjadi
penyebab kenapa Sumbar terus didera bencana ekologis.
“Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus
sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Hal ini
memperkuat dugaan bahwa praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi
penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang
terjadi di Sumbar menempatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi
Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya
dari risiko bencana.”
Uli Arta Siagian,
Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional mengatakan, dari fakta ini kita
bisa lihat dengan jelas bahwa penyebab bencana ekologis yang terjadi saat ini
adalah pengurus negara dan korporasi. Maka tanggung jawab pengurus negara
adalah mengevaluasi seluruh izin perusahaan yang ada di Indonesia, terkhususnya
di ekosistem penting dan genting.
“Jika harus dilakukan pencabutan izin, maka itu harus
dilakukan. Apalagi Menteri Kehutanan sudah bilang akan mengevaluasi, ya
sekarang kami tagih, kami punya nama-nama perusahaannya, silahkan evaluasi dan
lakukan penegakan hukum. Jangan hanya berjanji di tengah ratusan ribu orang
tengah berduka di Sumatera.”
“Hal lainnya adalah menagih pertanggungjawaban korporasi
untuk menanggung biaya eksternalitas dari bencana yang terjadi. Negara tidak
boleh menanggung biaya eksternalitas itu sendiri, karena uang yang akan dipakai
adalah uang negara yang sumbernya dari pajak kita. Menurut kami negara juga
harus menagih tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem yang telah
mereka rusak. Mereka telah menikmati keuntungan besar dari eksploitasi alam,
saatnya mereka juga ditagih tanggungjawab untuk memulihkannya.”
Gandar Mahojwala,
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta menyampaikan, BMKG telah menyatakan
bahwa 17 November telah dideteksi Pusat Tekanan Rendah (Low Pressure Area).
Pers rilis BMKG telah menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mulai
waspada atas potensi bencana hidrometeorologi.
Lalu, tanggal 21 November 2025, BMKG menyatakan bahwa Pusat
Tekanan Rendah telah menjadi Bibit Siklon. Kedua informasi ini menunjukkan
bahwa peringatan dini sudah cukup menjelaskan adanya potensi bencana, namun
tidak dilakukan aksi merespon peringatan dini yang serius oleh pemerintah.”
“Sebagaimana telah dijelaskan oleh WALHI Sumatera Utara,
Sumatera Barat, dan Aceh di media, bahwa bencana ini ada penyebab non-alamnya.
Pemicu utamanya bukan alam semata, tapi karena kerentanan yang disebabkan oleh
perusahaan-perusahaan yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini
menegaskan bahwa tidak ada yang namanya Bencana Alam. Istilah Bencana Alam
seolah membuat kambing hitam bencana ada pada alam. Padahal, proses terjadinya
bencana sangat dipengaruhi dari kerentanan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan
yang menguasai luas lahan yang besar,” jelas Gandar.
Ia melanjutkan, Pemerintah juga perlu tegas untuk segera
mengesahkan mekanisme Analisis Risiko Bencana, sebuah kegiatan penelitian dan
studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana. Analisis Risiko
Bencana sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (3), Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.
“Pasal ini menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang
mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis
risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan
kewenangannya. Instrumen ini menjadi penting untuk segera disahkan, untuk
memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang meningkatkan dan
memungkinkan terjadinya bencana,” tutup Gandar.
Melva Harahap, Manager Penanganan dan
Pencegahan Bencana Ekologis WALHI Nasional, juga menyampaikan, bahwa bencana
ekologis yang terjadi di Sumatera mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan di
3 provinsi tersebut. Rakyat mengalami kerugian material seperti kehilangan
rumah, keluarga, harta benda, hewan ternak, kebun, hak hidup dengan rasa aman
dan nyaman termasuk lingkungan hidup yang sehat hilang seketika ketika bencana
ekologis ini terjadi.
Di sisi lain, bencana ini juga mengakibatkan rusaknya sarana
prasana jalan rusak, listrik mati, sinyal komunikasi terputus, bbm langka,
bahan makanan semakin hari menipis, mengakibatkan warga terisolir. Hak bekerja,
hak belajar, dan kebutuhan dasar lain rakyat tidak dapat terpenuhi, padahal UU
24 tahun 2007 Tentang Kebencanaan, mewajibkan negara untuk melindungi rakyat
dari bencana yang terjadi fakta di lapangan hak dasar dan hidup yang menjadi
tanggung jawab negara tidak dapat memenuhinya.
“Dari sisi kemanusiaan, penetapan status bencana nasional
menjadi penting dalam merespon bencana ekologis yang terjadi di Sumatera.
Koordinasi antar Lembaga/Kementerian penting sehingga distribusi kebutuhan
pokok, mengevakuasi warga yang masih terisolir, memastikan kebutuhan dasar dan
hidup warga terjamin termasuk menyiapkan pemulihan jangka panjang bisa lebih
cepat karena penetapan status bisa membuka pergerakan sumber daya nasional
penuh dalam merespon bencana ekologis tersebut.”
“Tetapi hal yang harus diingat, penting bagi negara untuk
menagih pertanggungjawaban korporasi, dan tidak menetapkan ini sebagai bencana
alam, sebab penetapan itu akan berkonsekuensi pada gugurnya tanggungjawab
korporasi,” tutur Melva.
Ke depan, bencana ekologis juga akan terus meluas dan
semakin sering terjadi akibat kebijakan iklim yang tidak ambisius dan berbasis
HAM, bahkan justru mendorog pelepasan emisi dalam skala besar dari
proyek-proyek energi.
Keputusan-keputusan dalam COP30, terutama yang memajukan
solusi palsu di sektor energi dan memperluas mekanisme perdagangan karbon,
dikhawatirkan akan membuat bencana ekologis di Indonesia semakin sering dan
meluas karena pendekatan tersebut tidak mengurangi ketergantungan pada energi
fosil. Malah berpotensi memperparah perampasan ruang hidup serta kerusakan
ekosistem, dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk melakukan
pengurangan emisi secara nyata.
“Oleh karena itu kami menegaskan bahwa skema offset dan
teknologi semu tersebut justru membuka jalan bagi intensifikasi krisis iklim,
mulai dari deforestasi hingga peningkatan risiko bencana hidrometeorologis dan
menyerukan transisi energi yang adil, berbasis perlindungan lingkungan serta
hak-hak masyarakat, sebagai satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran
ekologis yang lebih besar di Indonesia.”

1.jpg)


.jpg)